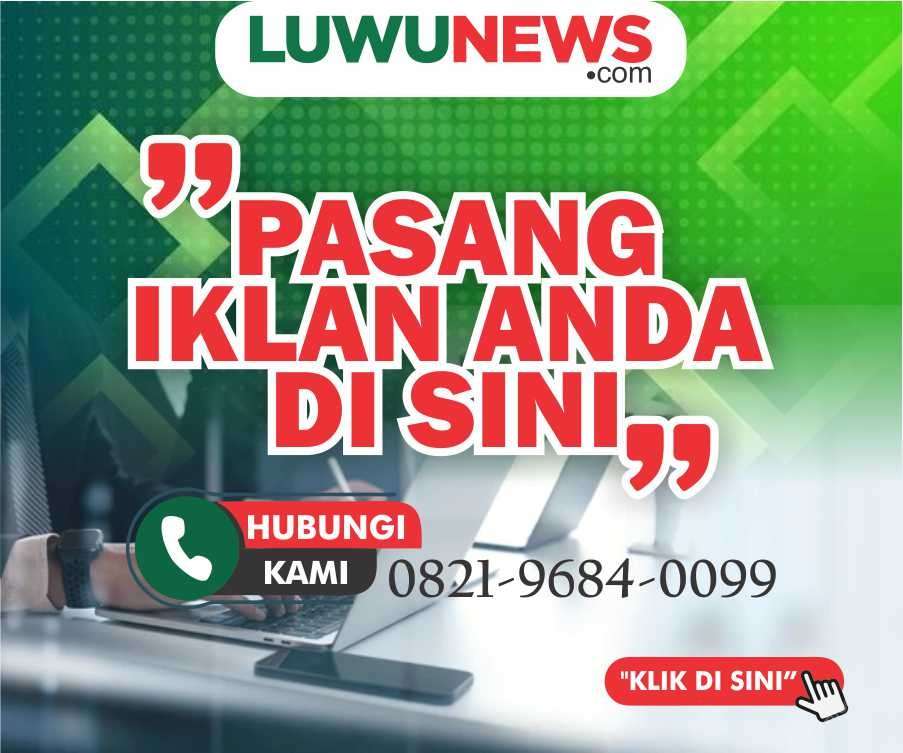Daerah Istimewa Luwu, Janji Negara Sejak Hari-Hari Pertama Republik

TIDAK semua wilayah bergabung ke dalam Republik Indonesia melalui proses yang sama.
Ada yang melalui peperangan panjang, ada yang melalui diplomasi berliku, dan ada pula yang memilih jalan paling sunyi namun paling bermakna, yakni bergabung tanpa syarat. Luwu berada pada kategori terakhir.
Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, Datu Luwu Andi Djemma secara tegas menyatakan pengakuan terhadap kedaulatan Republik Indonesia dan meleburkan Kerajaan Luwu ke dalam NKRI tanpa syarat apa pun.
Tidak ada negosiasi kekuasaan, tidak ada permintaan konsesi politik. Keputusan itu lahir murni dari keyakinan bahwa Republik adalah jalan sejarah bangsa.
Fakta ini penting ditegaskan, karena dari sinilah akar Daerah Istimewa Luwu (DIL) bermula yang kini bertransformasi menjadi Provinsi Luwu Raya.
Luwu bukan wilayah yang “dipaksa” masuk republik, melainkan pendiri moral republik di kawasan timur Indonesia. Datu Andi Djemma menyerahkan kedaulatan kerajaan yang telah berdiri ratusan tahun, bahkan sebelum Indonesia ada sebagai negara.
Pengorbanan politik itulah yang kemudian melahirkan janji Presiden Soekarno pada tahun 1950: Luwu akan diberi status Daerah Istimewa. Janji tersebut bukan hadiah, melainkan pengakuan negara atas pilihan sejarah Luwu.
Delapan tahun kemudian, 1958, Andi Djemma menagih janji itu langsung kepada Soekarno. Presiden tidak menolak. Ia hanya menyatakan bahwa realisasi DIL harus menunggu kondisi keamanan di Luwu pulih pasca pemberontakan Kahar Muzakkar. Negara kembali menempatkan stabilitas sebagai alasan penundaan.
Namun sejarah bergerak lebih cepat dari birokrasi negara. Tahun 1963, Andi Djemma wafat, membawa serta kegundahan tentang janji yang tak sempat ia saksikan terwujud. Sebelum wafat, ia meninggalkan wasiat politik: perjuangan Daerah Istimewa Luwu tidak boleh berhenti.
Estafet itu pertama kali dilanjutkan oleh Abdul Rahman Ba’, yang ditunjuk langsung oleh Andi Djemma. Tetapi negara kembali menghadirkan dalih baru. Situasi politik nasional pasca G30S/PKI dijadikan alasan bahwa stabilitas negara belum memungkinkan pembahasan DIL. Upaya itu kembali gagal.
Tahun 1967, amanah tersebut diteruskan oleh Andi Rompe Gading, Bupati Luwu, bersama wakilnya Andi Pali. Momentum seharusnya terbuka. Namun kekuasaan berbicara lain.
Andi Rompe Gading diberhentikan dari jabatannya dan dimutasikan ke Makassar, sementara Andi Pali dinonaktifkan. Perjuangan DIL kembali dipatahkan, bukan oleh konstitusi, melainkan oleh keputusan politik.
Era berganti, rezim runtuh, dan reformasi datang. Tahun 1999, Andi Kaso kembali menghidupkan wasiat Andi Djemma di tengah euforia otonomi daerah. Untuk sesaat, harapan tampak nyata. Namun perjuangan itu kembali terhenti karena Andi Kaso wafat sebelum agenda DIL mencapai tahap final.
Tahun 2004, upaya serupa dilanjutkan oleh Rakhmat Soedjono. Kali ini, hambatan bukan lagi negara pusat, melainkan resistensi elite lokal. Ketua DPRD Luwu Timur dan Luwu Utara menolak gagasan DIL. Ironisnya, ketika ruang demokrasi terbuka, justru kepentingan politik jangka pendek menutup jalan sejarah.
Maka hingga hari ini, Daerah Istimewa Luwu tetap hidup sebagai janji yang tertunda. Bukan karena kekurangan dasar sejarah. Bukan pula karena lemah secara konstitusional. Tetapi karena negara terus menunda keberanian untuk menepati janjinya sendiri.
Kini kita berdiri di ambang waktu baru. Tahun 2026.
Pertanyaan ini bukan sekadar penanda kalender. Ia adalah pertanyaan etis bagi republik: sampai kapan negara mengabaikan wilayah yang sejak hari-hari pertama kemerdekaan memilih Indonesia tanpa syarat?
Jika keistimewaan diberikan kepada daerah yang memiliki kekhususan sejarah, maka Luwu telah memenuhi syarat itu bahkan sebelum republik sepenuhnya berdiri. Yang tersisa hari ini bukan lagi soal kelayakan Luwu, melainkan kesungguhan negara menunaikan hutang sejarahnya.
Dan sejarah, seperti janji, pada akhirnya akan selalu menagih.(*)